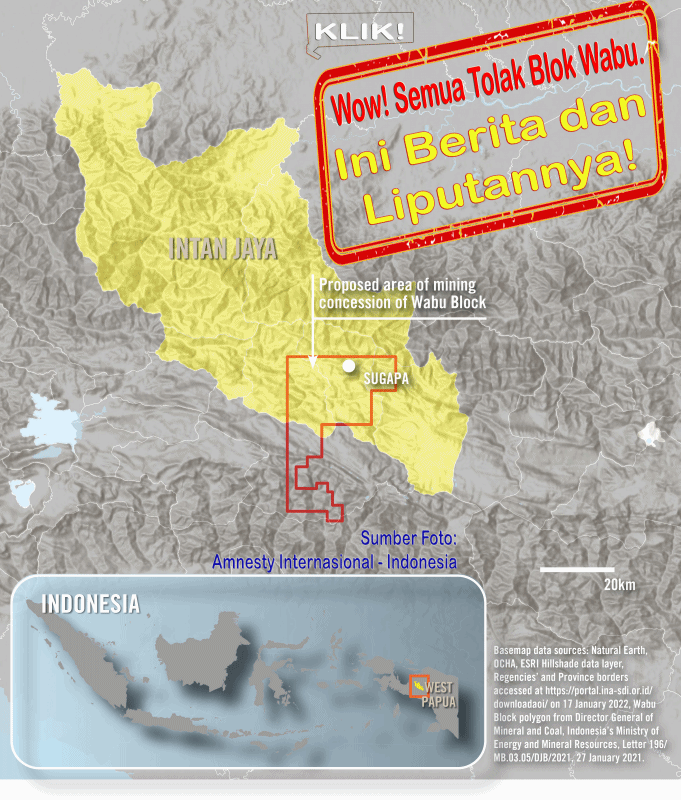|
| Foto: ilust/nn |
Papua sejak dulu sudah dipandang dengan tatapan colonial: Orang Papua itu terbelakang, primitif, tidak beradab. Karena itu, misi para penjelajah eropa ke Papua, misi pemerintahan Belanda dan yang lebih parah, Indonesia hingga kini, dan misi penyebaran agama dimaksudkan untuk memajukan, memodernkan, membuat beradab suku-suku bangsa di tanah Papua ini. Bila ko orang Papua asli: kou hitam, kou keriting, kou sudah mennyandang predikat terbelakang, primitif dan tidak beradab.
Narasi-narasi, kajian ilmiah, dan tulisan-tulisan telah ramai-ramai diproduksi mendukung rasisme ini. Pada akhirnya semua itu menjadi alat yang melegitimasi penghancuran kearifan, pengetahuan, kebudayaan dan semua perkakas adat yang dianggap perlambang keterbelakangan itu.
Berikut adalah tinjauan historis tentang bagaimana ‘orang luar’ memandang kita:
Tatapan colonial yang rasis ini mendasari doktrin hari ini bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada abat ke-13 dan -14 telah menguasai tanah Papua. Padahal, hubungan yang terbangun saat itu tidak secara langsung tetapi melalui Maluku, dan hanya bersifat perdagangan.
Tatapan colonial ini mendasari motivasi kontak orang Portugal dengan Papua. Berawal dari laporan Pigaffeta tentang pulau Papua yang dinamainya Isla de Oro (Pulau Emas), Alvaro de Saavedra diperintahkan oleh Herman Cortez (1529) dari Meksiko ke Maluku untuk mencari dan menaklukkan Isla de Oro. Karna gagal, Herman Cortez (1537) mengirim lagi Herman Griyalva untuk mencari Isla de Oro dan menaklukannya.
Tatapan colonial ini mendasari Kapten Ynigo Ortiz de Retes (20 Juni 1545) dengan kapalnya, San Juan, yang terdampar di sekitar muara Sungai Mamberamo itu lalu menamai tanah Papua sebagai Nova Guinea dan memproklamasikan bahwa pulau ini milik Raja Spanyol.
Tatapan colonial juga yang meladasari tindakan Kapten Torres proklamasikan sejumlah tempat di selatan Papua tahun 1606 sebagai milik Raja Spanyol.
Tatapan colonial ini mendasari kontak dan sejarah bangsa Papua bersama bangsa Belanda. Pada 1606, navigator Belanda Willen Janz, tiba di pantai selatan Papua dalam rangka mencari emas.Sepuluh tahun kemudian, Le Maire dan Scouten mengikutinya, menjelajahi teluk Cendrawasih ketemu pulai Biak, dan seterusnya, hanya untuk mencari sesuatu yang bernilai jual bagi pasar eropa, tentu saja dengan penaklukan, perampokan.
Tatapan colonial juga mendasari kedatangan bangsa Prancis (1768), Inggris (1770) dan Jerman (1799) ke tanah Papua. Motivasi mereka sama: mencari sesuatu yang berharga untuk diperdagangkan di pasar eropa, tentu saja dengan jalan merampas, merampok, monopoli perdagangan.
Tatapan colonial juga mendasari penyebaran agama Katolik, Protestan dan Islam di tanah Papua. Agama barat dipaksakan untuk dianut oleh orang Papua tanpa konteks: lalu semua agama adat harus dihapuskan, perkakas dan peralatan keagamaan dibakar, semua upacara-upacara agama adat dibatasi dan dihentikan paksa, lalu orang Papua dipaksa menjadi penganut Katolik dan Protestan persis sesuai dengan tata-cara orang barat. Padahal, agama adat di Papua sebelumnya juga menjadi semacam saluran perekat keharmonisan dan kesinambungan hidup dengan alam dan sebagai sarana mengatasi berbagai persoalan lokal.
Tatapan colonial juga mendasari pasar budak orang Papua di Banda, juga di Rambati, yang didominasi orang Seram dan Goram sekitar tahun 1700-1800-an. Setiap tahun, orang Seram dan Goram mendatangi kampung-kampung orang Papua sekitar Fak-Fak, Berau, Onim, Kowiyai, dan daerah-daerah sekitarnya, menyerang kampung-kampung orang Papua, menghancurkan semua rumah, bakar, dan orang-orang Papua ditangkap untuk dijual sebagai budak. Orang dari Ternate-Tidore, Makassar, Bugis, Buton, datang beli budak orang Papua di pasar-pasar ini, untuk dipakai atau untuk kemudian dijual lagi.
Tatapan colonial ini melandasi argumentasi Mohammad Yamin dalam rapat BPUPKI pada 11 Juli 1945, dimana dirinya ngotot agar Papua menjadi bagian dari Indonesia merdeka, karna menurutnya, secara etnologis, Papua termasuk bangsa Indonesia, dan punya kekayaan alam yang dapat menguntungkan Indonesia.
Tatapan colonial juga melandasi argumentasi Soekarno, yang mengatakan kepada Jendral Hasaichi Taraci pada 12 Agustus 1945 bahwa bangsa Papua masih primitif dan terbelakang, dan tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan Papua.
Tatapan colonial juga melandasi ditetapkannya Papua sebagai bagian dari NKRI, padahal belum satu pun orang Papua berpartisipasi dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
Tatapan colonial juga melandasi proses Konfrensi Meja Bundar (KMB) 1949, dimana proses pembahasan tentang Papua sama sekali tanpa melibatkan wakil rakyat Papua, bahkan tanpa orang Papua tahu: mereka membahasnya seakan-akan Papua tanah yang tak berpenghuni.
Tatapan colonial juga melandasi dikeluarkannya TRIKORA (Tiga pendapat rakyat: Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buaatan Belanda Kolonial; Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat; Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kesatuan tanah air dari Sabang-Merauke) pada 19 Desember 1961, dimana NKRI tidak mengakui keberadaan, tidak menghargai dan menghormati keputusan politik rakyat bangsa Papua untuk merdeka, melalui deklarasi Negara pada 1 Desember 1961.
Tatapan colonial juga ada di dalam pembentukan Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962, dimana NKRI sudah mulai menggalang daya upaya mencaplok Papua dengan kekuatan bersenjata.
Tatapan colonial juga mendasari tindakan Negara Indonesia sehari dua hari setelah penyerahan kekuasaan dari UNTEA ke NKRI, tanggal 3-4 Mei 1963: Indonesia membakar habis tanpa sisa semua buku, dokumen, sketsa dan gambar tentang Papua (manusia, kebudayaan dan sejarahnya) di Jayapura dengan maksud membasmi sejarah bangsa Papua.
Tatapan colonial juga melandasi aksi NKRI membungkam aspirasi politik bangsa Papua dengan gelombang penangkapan, pemenjarahan, penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh politik Papua sejak 1962-1969.
Tatapan colonial mendasari tindakan Negara Indonesia merampok semua barang-barang peninggalan Belanda di Jayapura dan sekitarnya tahun 1962-1963, mobil dan motor, termasuk kain horden dan botol-botol bekas.
Tatapan colonial juga ada di dalam penyelenggaraan PEPERA 1969, dimana hak rakyat Papua untuk opsi menentukan nasib sendiri tidak menjadi pilihan; juga one man one vote tidak dihargai dan dibungkam dengan musyawarah-mufakat: sebuah cara NKRI untuk merekayasa suara rakyat Papua, dimana 1025 orang yang sudah dipengaruhi NKRI saja yang memilih mewakili skitar 800 ribu orang Papua saat itu.
Tatapan colonial juga ada di balik dibungkam dan dihancurkannya melalui perang dan diplomasi, semua hal yang berhubungan dengan Proklamasi 1 Juli 1971 oleh OPM di desa Waris, Jayapura.
Tatapan colonial juga ada di balik dibunuhnya Dr. Thom Wanggai dari penjara Cipinang pada 1986; dikucilkan, gerakannya ditumpas dengan senjata, dan tidak mengutamakan jalan damai.
Tatapan colonial juga ada di balik berbagai isu pelanggaran HAM yang ada di Papua: Uncen Berdarah, Wamena Berdarah, Paniai Beradarah, Biar Berdarah, Wasior Berdarah, Nabire Berdarah, dan semua yang lainnya: semua kasus pelanggaran HAM itu sengaja didiamkan, tidak diselesaikan, oleh karena NKRI menganggap rendah hak hidup dan harkat/martabat orang Papua.
Tatapan colonial juga ada di balik kurikulum pendidikan sentralistik yang diterapkan di Papua hingga kini: dimana pendidikan pancasila, pendidikan bela Negara, pendidikan integritas NKRI menjadi yang utama didoktrin dibanding pelajaran yang lain. Lebih-lebih soal kearifan lokal Papua yang tidak boleh ada di dalam kurikulum pendidikan (terutama soal sejarah Papua yang sebenarnya).
Tatapan colonial juga ada di balik program transmigrasi: orang-orang luar Papua didatangkan besar-besaran untuk memberi orang Papua pelajaran bagaimana hidup yang beradab. Para transmigran harus mengajari orang Papua membuat sawah, hidup menurut tata cara dan budaya pendatang, karena menanggap tata cara dan budaya orang Papua mewakili zaman batu yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, di awal-awal, orang Papua asli dan atau beberapa suku bangsa Papua diapit oleh banyaknya transmigran, sehingga diharapkan orang asli Papua hidup dan berperilaku laiknya pendatang yang menjadi cermin modernitas.
Tatapan colonial juga ada di balik program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-V yang digalang Orde Baru RI. Dimana Papua dipandang sebagai objek yang seperti kertas kosong yang harus diisi, diajari, dibangun oleh Negara, bahkan dengan kekerasan: semua orang Papua yang mempertahankan eksistensi diri sebagai Papua dianggap separatis dan berhak dibunuh.
Tatapan colonial juga ada di balik semua eksploitasi SDA: Emas, minyak bumi dan gas alam, hutan, dan perkebunan sawit-padi dalam rupa perusahaan-perusahaan nasional dan multi nasional. Negara menugaskan militernya untuk menjaga aset-aset para pemodal ini sehingga, rakyat Papua yang melawan harus berhadapan dengan militer bila melawan dan diharuskan mati pasrah menerima nasib dijajah.
Tatapan colonial juga ada di balik tidak didengarkannya aspirasi bangsa Papua melalui Tim 100 yang bertemu dengan Presiden RI, dan pemaksaan paket Otsus yang tidak diminta orang Papua.
Tatapan colonial juga ada di balik berbagai pemekaran yang saat ini marak untuk mengerjakan dan membangun semua syarat bagi diekspolitasinya tanah air dan semua yang dikandung Papua ini, yakni hendak membagi tanah Papua menjadi lima provinsi. Padahal, rakyat Papua menolaknya karena merasa diri belum siap.
Tatapan colonial juga ada di balik ujaran rasis yang dialami orang Papua: terhadap mahasiswa Papua di luar Papua yang dipanggil kete, wong ireng, monyet, kotor, kasar, bau, kanibal, malas, suara besar, tidak bertanggungjawab, bodoh, primitive, terbelakang, manusia zaman batu.
Tatapan colonial ini ada di balik semua hal berbau rasis yang dialami orang Papua di luar Papua.
Tatapan colonial juga ada di balik semua perlakuan rasis yang dialami orang Papua yang ada di pemerintahan, terhadap gubernur, para bupati dan walikota di Papua kala berhadapan dengan Jakarta; Jakarta selalu menempatkan diri sebagai pihak yang lebih paham, yang lebih cerdas, yang lebih lihai, yang lebih mampu, sebagai guru, sebagai manusia, yang hendak/berusaha/ingin membantu bangsa Papua agar menjadi sama seperti mereka, agar Papua menjadi beradab, terbangun, maju, dan modern seperti mereka.
Silahkan ditambahkan lagi contoh-contoh lainnya di kolom komentar.
Semua ini menjadi bukti bagaimana dari dulu hingga kini, orang Papua dipandang sebagai orang kelas dua di Indonesia ini, yang selalu, selalu, membutuhkan NKRI untuk menjadi manusia. Namun, sebaik apa pun, sehebat apa pun, usaha, kepintaran, budi, marifat, kou orang Papua dalam hal menjadi seperti Indonesia, kou akan tetap dipandang sebagai Papua yang ada di kelas dua.
Karna itu kou harus merdeka secara politik dan mandiri secara ekonomi untuk menjadi dirimu sendiri: Bangsa Papua.
Penulis adalah Editor media ini, https://www.tadahnews.com/